Menggulingkan Stereotip Negatif Masyarakat terhadap Jurusan Sastra Idonesia
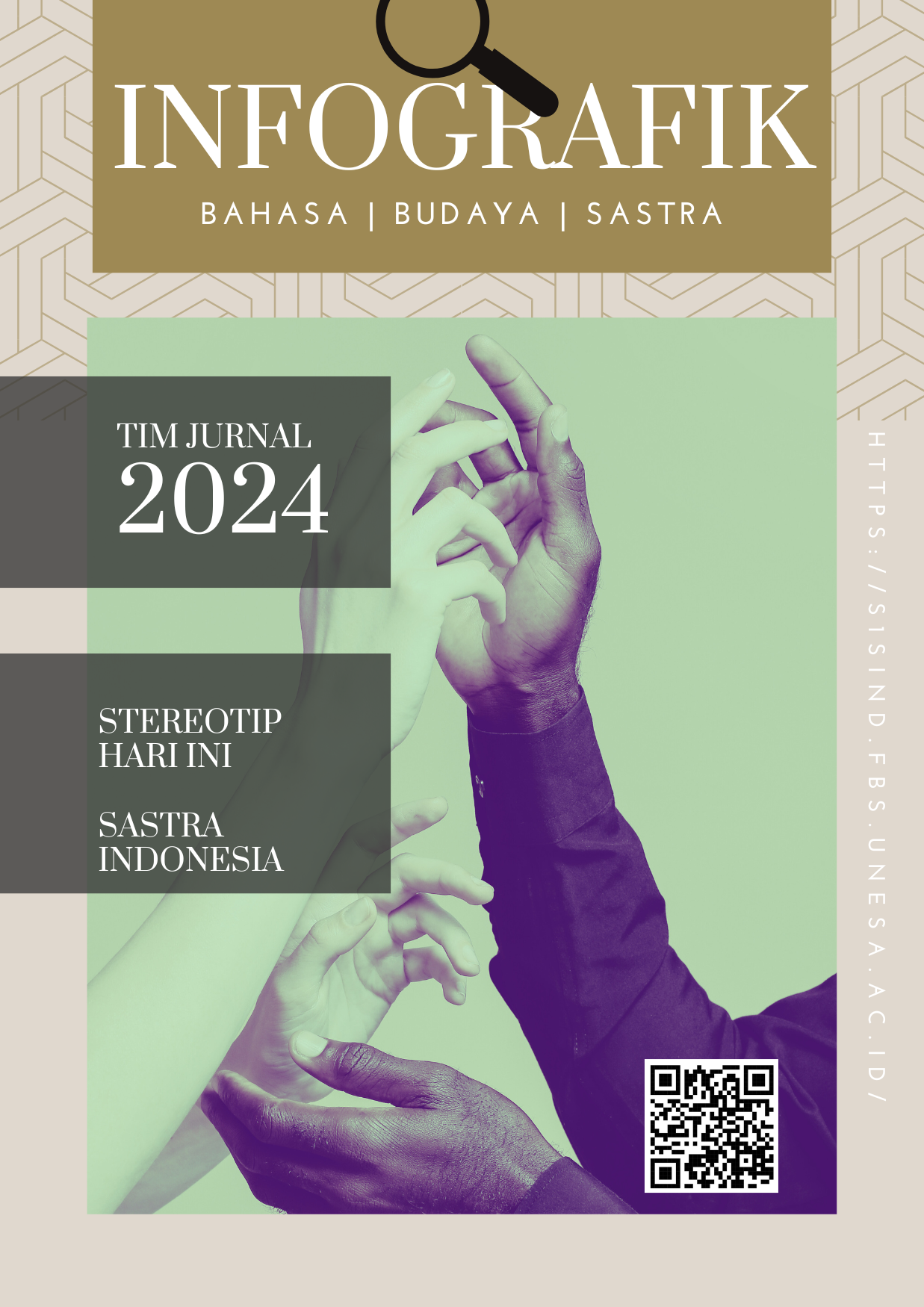
Sudah
menjadi hal yang biasa masyarakat memandang rendah jurusan sastra, terlebih
Sastra Indonesia yang kerap disebut sebagai sastra lokal. Sudah bisa bahasa
Indonesia, ngapain ambil jurusan Sastra Indonesia? Kalau lulus mau kerja jadi
apa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin sudah sering menyambangi
telinga para mahasiswa Sastra Indonesia. Lantas, mengapa di Indonesia jurusan
sastra cenderung memeroleh stereotip negatif dari masyarakat? Sastra dipandang
sebagai kebutuhan tersier manusia. Lulusan sastra dianggap tidak menduduki
pilar utama bidang profesi pokok dan vital seperti bidang kesehatan, ekonomi, atau
ilmu komputer. Sastra juga bersifat abstrak. Tidak pasti. Satu ditambah satu
tidak selalu sama dengan dua sebagaimana pada ilmu matematika, namun bisa jadi
tiga, empat, dan seterusnya. Selain itu, sastra dianggap hanya berkutat pada
puisi, cerpen, dan novel yang bisa ditekuni secara mandiri atau otodidak. Inferioritas
masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai luhur budaya juga turut mengakibatkan
sastra kurang dilirik di negeri ini.
Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Anggapan bahwa lulusan sastra kurang dibutuhkan di masa depan sepenuhnya keliru. Justru, lulusan sastra dan bahasa memiliki peluang karier yang gemilang di masa depan selama manusia masih berbahasa. Hal ini dikarenakan pada jurusan sastra, mahasiswa akan dilatih untuk terampil dalam berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan berbahasa yang kuat akan sangat dibutuhkan dalam bidang media, jurnalistik, penerjemahan, dan industri kreatif. Bahkan sastra juga dapat memengaruhi sektor perekonomian, khususnya pada industri film dan televisi. Banyak sekali film atau serial yang diadaptasi dari karya sastra. Seperti film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, Sang Penari, Hujan Bulan Juni, Bumi Manusia, dan Gadis Kretek. Adaptasi tersebut tentu memunculkan peluang bagi penulis naskah, sutradara, rumah produksi, hingga aktor.

Selain
itu sastra juga bersifat abstrak, dapat menghadirkan interpretasi yang beraneka
ragam tergantung pada sudut pandang orang yang menafsirkannya. Namun, justru
karena keabstrakan tersebutlah mahasiswa sastra terlatih untuk menjadi sosok
yang kritis, kreatif dan imajinatif. Terlebih pada jurusan ini, mahasiswa
diberi kebebasan untuk berpikir dalam memahami relita dan imajinasi. Kebebasan berpikir ini menuntut mahasiswa
sastra untuk mencari makna dan kemungkinan-kemungkinan tersembunyi, hingga
melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Hal tersebut tentu akan sangat
bermanfaat di masa depan, khususnya di era globalisasi yang sarat akan
perubahan dan tantangan ini.
Pandangan
rendah jurusan sastra mungkin juga disebabkan karena angggapan bahwa sastra
hanya belajar puisi, cerpen, dan novel yang bisa ditekuni secara mandiri atau
otodidak. Padahal, sastra lebih luas dari sekadar mengkaji Aku Ingin-nya
Sapardi, Tragedi Winka dan Sihka-nya Sutardji, Robohnya Surau Kami-nya
A.A. Navis, atau Siti Nurbaya-nya Marah Roesli. Tidak, sastra jauh lebih
luas daripada itu semua. Selain mempelajari seluk-beluk bahasa, karya sastra,
hingga teori-teorinya, mahasiswa sastra juga terlibat dalam berbagai bidang
yang kaya dan beragam, termasuk filsafat, sosiologi, bahkan psikologi. Dengan
filsafat, mahasiswa sastra belajar berpikir dan melukiskan pemikirannya melalui
kekayaan dan keindahan bahasa. Dengan sosiologi, mahasiswa sastra menekuni
sosial dan budaya yang penuh dengan perubahan. Dan dengan psikologi, mahasiswa
sastra menjelajahi kejiwaan karakter-karakter manusia. Dengan demikian,
mahasiswa sastra tentu terlatih seni untuk memanusiakan manusia karena
seringkali mereka dihadapkan pada kondisi untuk memahami bagaimana kompleksitas
dan keanekaragaman manusia.
Lebih
dari itu, sastra juga memegang peranan yang krusial untuk zaman yang akan
datang. Ya, sastra adalah dokumenter sejarah. Sastra dapat merekam kehidupan
umat manusia serta mencerminkan realitas sosial dan budaya pada zamannya. Tentunya
dengan kekayaan dan keindahan bahasa. Sebut saja novel kondang Bumi Manusia
karya Pramoedya Ananta Toer yang menggambarkan realitas masyarakat Indonesia di
masa kolonial. Melalui novel tersebut, generasi pada zaman ini dapat mengetahui
bagaimana kehidupan Bangsa Indonesia di rentang tahun 1898 hingga 1918. Lantas,
untuk apa suatu generasi perlu mengetahui sejarah sosial dan budaya masa
lampau? Tentu agar mereka dapat belajar dari pengalaman dan memanfaatkannya
sebagai bekal untuk melanjutkan peradaban.
Menyala mahasiswa Sastra Indonesia! (Penulis : Assa'idah Silva Amalia)
- Tim Jurnal 2024 -